Artikel ini Lanjutan dari Menyikapi Hadits Lemah (bag.1). Jika Belum Membacanya, silakan klik di Sini.
Penjelasan dari Ibnu Taimiyah
Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan, “Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan bolehnya menjadikan sesuatu yang wajib atau sunnah berdasarkan hadits dho’if. Barangsiapa menyatakan bolehnya hal itu, maka sungguh ia telah menyelisihi ijma’ (kesepakatan para ulama). Hal ini sama halnya ketika kita tidak boleh mengharamkan sesuatu (dalam masalah hukum) kecuali berdasarkan dalil syar’i (yang shahih). Akan tetapi jika diketahui sesuatu itu terlarang (haram) dari hadits yang membicarakan balasan baik bagi pelakunya dan diketahui bahwa hadits tersebut bukan diriwayatkan oleh perowi pendusta, maka hadits tersebut boleh saja diriwayatkan dalam rangka targhib (memotivasi dalam amalan kebaikan) dan tarhib (untuk menakut-nakuti). Hal ini berlaku selama tidak diketahui bahwa hadits tersebut adalah hadits yang berisi perowi pendusta (baca: hadits maudhu’/palsu). Namun patut diketahui bahwa memotivasi suatu amalan kebaikan atau menakuti-nakuti dari suatu amalan yang jelek didukung dengan dalil lain (yang shahih), bukan hanya dengan hadits yang tidak jelas status keshahihannya.” [Majmu’ Al Fatawa, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni, 1/ 251, Darul Wafa’]
Ada dua point berharga yang bisa kita ambil dari penjelasan Syaikhul Islam di atas. Pertama, tidak boleh menggunakan hadits maudhu’ (hadits palsu yang berisi perowi pendusta) dalam masalah targib dan tarhib. Kedua, hadits dho’if yang digunakan untuk memotivasi dalam beramal, hendaknya memiliki landasan dari hadits shahih lainnya. Sehingga sebenarnya yang kita amalkan adalah hadits shahih dan bukan hadits dhoifnya.
Di tempat yang lain Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Jika diketahui bahwa suatu amal disunnahkan dengan dalil syar’i (dalil shahih) dan diriwayatkan pula hadits lainnya dengan sanad yang dho’if yang membicarakan masalah fadhilah amal, maka hadits tersebut bisa diriwayatkan asalkan haditnys bukan merupakan hadits maudhu’ (yang di dalamnya ada salah satu perowi pendusta). Karena yang namanya jumlah pahala (dalam memotivasi untuk beramal, pen) tidak diketahui ukuran pastinya. Oleh karenanya, jika dalam masalah ukuran pahala diriwayatkan dengan hadits yang dho’if selama bukan hadits yang dusta (hadits maudhu’), maka hadits semacam ini tidak dikatakan dusta. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hambal dan ulama lainnya memberikan keringanan meriwayatkan hadits dhoif dalam masalah fadhoil a’mal. Adapun jika suatu amalan dikatakan sunnah berdasarkan hadits dho’if (semata), maka beliau menjauhkan diri darinya karena (takut pada) Allah.”[Majmu’ Al Fatawa, 10/408-409]
Beliau menjelaskan pula, “Jika hadits dho’if tentang fadhilah amal mengandung amalan yang disebutkan tata cara tertentu atau jumlah tertentu –seperti disebutkan shalat pada waktu tertentu dengan bacaan tertentu atau tata cara tertentu-,maka hadits semacam ini tidak boleh diamalkan. Karena tata cara amalan yang dilakukan haruslah ditetapkan dengan dalil syar’i. Hal ini berbeda halnya jika diriwayatkan suatu hadits yang mengatakan bahwa barangsiapa memasuki pasar lalu ia menyebut “laa ilaha ilallah”,
Beliau menjelaskan pula, “Jika hadits dho’if tentang fadhilah amal mengandung amalan yang disebutkan tata cara tertentu atau jumlah tertentu –seperti disebutkan shalat pada waktu tertentu dengan bacaan tertentu atau tata cara tertentu-,maka hadits semacam ini tidak boleh diamalkan. Karena tata cara amalan yang dilakukan haruslah ditetapkan dengan dalil syar’i. Hal ini berbeda halnya jika diriwayatkan suatu hadits yang mengatakan bahwa barangsiapa memasuki pasar lalu ia menyebut “laa ilaha ilallah”, maka pahalanya sekian dan sekian, maka ini tidak mengapa. Karena yang namanya dzikir kepada Allah di pasar disunnahkan karena ini termasuk amalan yang dilakukan di saat kebanyakan orang sedang lalai.”[Majmu’ Al Fatawa, 18/67]
Ibnu Taimiyah kemudian membuat kesimpulan yang amat bagus dalam perkataan selanjutnya,
. ِّيِعْرَّشلا ِليِلَّدلا ىَلَع ُفَّقَوَتَي ِباَقِعْلاَو ِباَوَّثلا ُريِداَقَم َوُهَو ِهِبِجوُم ُداَقِتْعا َّمُث ِباَبْحِتْساِلا يِف اَل ِبيِهْرَّتلاَو ِبيِغْرَّتلا يِف ِهِب ُلَمْعُيَو ىَوْرُي َباَبْلا اَذَه َّنَأ : ُلِصاَحْلاَف .
“Intinya, hadits dho’if bisa diriwayatkan namun dalam masalah targhib dan tarhib saja. Hadits dho’if bukanlah diriwayatkan untuk menyebutkan sunnahnya suatu amalan. Adapun untuk memastikan besarnya suatu pahala atau akibat buruk dari suatu amalan jelek, maka cukup dalil syar’i (yang shahih) yang jadi pegangan. ”[Majmu’ Al Fatawa, 18/68]
Sikap yang Lebih Hati-Hati
Sebagian ulama bersikap bahwa hadits dho’if tidak boleh digunakan secara mutlak kecuali jika ingin dijelaskan dho’ifnya. Pendapat ini tidak diragukan lagi lebih hati-hati dan lebih selamat. Untuk memotivasi pada kebaikan dan mengancam suatu perbuatan yang jelek sebenarnya sudah cukup dengan hadits shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Demikian pembahasan mengenai Menyikapi Hadits Lemah (bag.2). Semoga bermanfaat.
 |
| menyikapi hadits lemah |
Penjelasan dari Ibnu Taimiyah
Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan, “Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan bolehnya menjadikan sesuatu yang wajib atau sunnah berdasarkan hadits dho’if. Barangsiapa menyatakan bolehnya hal itu, maka sungguh ia telah menyelisihi ijma’ (kesepakatan para ulama). Hal ini sama halnya ketika kita tidak boleh mengharamkan sesuatu (dalam masalah hukum) kecuali berdasarkan dalil syar’i (yang shahih). Akan tetapi jika diketahui sesuatu itu terlarang (haram) dari hadits yang membicarakan balasan baik bagi pelakunya dan diketahui bahwa hadits tersebut bukan diriwayatkan oleh perowi pendusta, maka hadits tersebut boleh saja diriwayatkan dalam rangka targhib (memotivasi dalam amalan kebaikan) dan tarhib (untuk menakut-nakuti). Hal ini berlaku selama tidak diketahui bahwa hadits tersebut adalah hadits yang berisi perowi pendusta (baca: hadits maudhu’/palsu). Namun patut diketahui bahwa memotivasi suatu amalan kebaikan atau menakuti-nakuti dari suatu amalan yang jelek didukung dengan dalil lain (yang shahih), bukan hanya dengan hadits yang tidak jelas status keshahihannya.” [Majmu’ Al Fatawa, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni, 1/ 251, Darul Wafa’]
Ada dua point berharga yang bisa kita ambil dari penjelasan Syaikhul Islam di atas. Pertama, tidak boleh menggunakan hadits maudhu’ (hadits palsu yang berisi perowi pendusta) dalam masalah targib dan tarhib. Kedua, hadits dho’if yang digunakan untuk memotivasi dalam beramal, hendaknya memiliki landasan dari hadits shahih lainnya. Sehingga sebenarnya yang kita amalkan adalah hadits shahih dan bukan hadits dhoifnya.
Di tempat yang lain Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Jika diketahui bahwa suatu amal disunnahkan dengan dalil syar’i (dalil shahih) dan diriwayatkan pula hadits lainnya dengan sanad yang dho’if yang membicarakan masalah fadhilah amal, maka hadits tersebut bisa diriwayatkan asalkan haditnys bukan merupakan hadits maudhu’ (yang di dalamnya ada salah satu perowi pendusta). Karena yang namanya jumlah pahala (dalam memotivasi untuk beramal, pen) tidak diketahui ukuran pastinya. Oleh karenanya, jika dalam masalah ukuran pahala diriwayatkan dengan hadits yang dho’if selama bukan hadits yang dusta (hadits maudhu’), maka hadits semacam ini tidak dikatakan dusta. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hambal dan ulama lainnya memberikan keringanan meriwayatkan hadits dhoif dalam masalah fadhoil a’mal. Adapun jika suatu amalan dikatakan sunnah berdasarkan hadits dho’if (semata), maka beliau menjauhkan diri darinya karena (takut pada) Allah.”[Majmu’ Al Fatawa, 10/408-409]
Beliau menjelaskan pula, “Jika hadits dho’if tentang fadhilah amal mengandung amalan yang disebutkan tata cara tertentu atau jumlah tertentu –seperti disebutkan shalat pada waktu tertentu dengan bacaan tertentu atau tata cara tertentu-,maka hadits semacam ini tidak boleh diamalkan. Karena tata cara amalan yang dilakukan haruslah ditetapkan dengan dalil syar’i. Hal ini berbeda halnya jika diriwayatkan suatu hadits yang mengatakan bahwa barangsiapa memasuki pasar lalu ia menyebut “laa ilaha ilallah”,
Beliau menjelaskan pula, “Jika hadits dho’if tentang fadhilah amal mengandung amalan yang disebutkan tata cara tertentu atau jumlah tertentu –seperti disebutkan shalat pada waktu tertentu dengan bacaan tertentu atau tata cara tertentu-,maka hadits semacam ini tidak boleh diamalkan. Karena tata cara amalan yang dilakukan haruslah ditetapkan dengan dalil syar’i. Hal ini berbeda halnya jika diriwayatkan suatu hadits yang mengatakan bahwa barangsiapa memasuki pasar lalu ia menyebut “laa ilaha ilallah”, maka pahalanya sekian dan sekian, maka ini tidak mengapa. Karena yang namanya dzikir kepada Allah di pasar disunnahkan karena ini termasuk amalan yang dilakukan di saat kebanyakan orang sedang lalai.”[Majmu’ Al Fatawa, 18/67]
Ibnu Taimiyah kemudian membuat kesimpulan yang amat bagus dalam perkataan selanjutnya,
. ِّيِعْرَّشلا ِليِلَّدلا ىَلَع ُفَّقَوَتَي ِباَقِعْلاَو ِباَوَّثلا ُريِداَقَم َوُهَو ِهِبِجوُم ُداَقِتْعا َّمُث ِباَبْحِتْساِلا يِف اَل ِبيِهْرَّتلاَو ِبيِغْرَّتلا يِف ِهِب ُلَمْعُيَو ىَوْرُي َباَبْلا اَذَه َّنَأ : ُلِصاَحْلاَف .
“Intinya, hadits dho’if bisa diriwayatkan namun dalam masalah targhib dan tarhib saja. Hadits dho’if bukanlah diriwayatkan untuk menyebutkan sunnahnya suatu amalan. Adapun untuk memastikan besarnya suatu pahala atau akibat buruk dari suatu amalan jelek, maka cukup dalil syar’i (yang shahih) yang jadi pegangan. ”[Majmu’ Al Fatawa, 18/68]
Sikap yang Lebih Hati-Hati
Sebagian ulama bersikap bahwa hadits dho’if tidak boleh digunakan secara mutlak kecuali jika ingin dijelaskan dho’ifnya. Pendapat ini tidak diragukan lagi lebih hati-hati dan lebih selamat. Untuk memotivasi pada kebaikan dan mengancam suatu perbuatan yang jelek sebenarnya sudah cukup dengan hadits shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Demikian pembahasan mengenai Menyikapi Hadits Lemah (bag.2). Semoga bermanfaat.
Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal
Artikel muslim.or.id (dengan sedikit editan dari admin blog)
Menyikapi Hadits Lemah (bag.2)
 Reviewed by IP Admin
on
4:15:00 AM
Rating:
Reviewed by IP Admin
on
4:15:00 AM
Rating:
 Reviewed by IP Admin
on
4:15:00 AM
Rating:
Reviewed by IP Admin
on
4:15:00 AM
Rating:

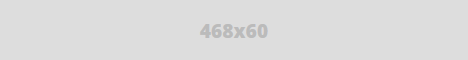









No comments:
Anda dapat berkomentar menggunakan identitas apa saja. Silakan berkomentar dengan baik dan sopan. Sepatah kata Anda bisa jadi sangat berarti bagi Blog ini, in syaa Allah.